*Oleh Yogyantoro, Pendidik di SMPN 4 Muara Teweh dan Narasumber Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional, Dikmen Diksus RI.
Tulisan ini pertama kali terbit di Media Indonesia.
Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 berbunyi ‘Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan’. Hal ini menegaskan bahwa setiap warga negara tidak ada diskriminasi (pembedaan perlakuan) untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik dalam kaitannya dengan pembelajaran di sekolah.
Indikator kualitas hidup peserta didik di sekolah meliputi to live, yaitu mendapatkan layanan pembelajaran yang akomodatif. Kemudian to love, yaitu memperoleh kasih sayang dan perlindungan. Termasuk to work, yaitu mendapatkan kesempatan untuk bekerja setelah lulus sekolah dan to play, yaitu berkesempatan untuk bermain bersama teman-temannya, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan perlombaan.
Indikator kualitas hidup sebagaimana tersebut tetap mengusung konsep keberagaman peserta didik, yaitu menghargai perbedaan kekuatan fisik, psiko, dan minat, menghapus stereotip gender dan mengakomodasi pluralitas horizontal seperti etnik atau subetnik dan pluralitas vertikal seperti pelapisan sosial. Sekolah yang menghargai perbedaan, meramahi, dan mengakomodasi kebutuhan anak disebut dengan sekolah inklusi. Sekolah yang inklusif menjamin kualitas hidup peserta didiknya, termasuk penyandang disabilitas atau peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK).
Pengelolaan tanpa diskriminasi
Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan, tanggung jawab, dan kewajiban yang sama. Badan Pusat Statistik mencatat ada 21 juta penyandang disabilitas atau 8,56% dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas belum terpenuhi atau tuntas.
PDBK membutuhkan pusat layanan anak-anak khusus dan penanganan secara khusus dengan berbagai terapi, seperti terapi okupasi, terapi berenang, terapi Alquran, terapi floor time (bermain di lantai), terapi perilaku metode applied behavior analysis (ABA), atau terapi sensory integration. Selain itu, mereka harus dipersiapkan untuk menjadi manusia-manusia yang mampu memasuki kehidupan normal, tanpa diskriminasi.
Oleh karena itu, pemerintah mendorong kebijakan yang lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas melalui program pemenuhan Sebagian, yaitu 5.000 guru pembimbing khusus (GPK). Tujuannya untuk mengajar di sekolah-sekolah umum yang kemudian dikenal dengan sekolah inklusi.
Peserta didik di sekolah inklusi ini terdiri atas peserta didik reguler, PDBK, dan peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Sekolah inklusi memperlakukan peserta didik melampaui makhluk ekonomi dengan kepentingannya, tapi mampu menyentuh hati, jiwa, dan sisi-sisi kemanusiaan dengan segenap daya kreasi, rasa empati, dan otonomi individu.
Penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolah inklusi berfokus pada kompetensi yang masih mungkin untuk dikembangkan atau program pembelajaran individual (one to one teaching). Tidak boleh menitikberatkan pada ketidakmampuan peserta didik.
Penekanan pada kerja sama daripada persaingan, kurikulum diferensial, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan menjadi elemen pendidikan di sekolah inklusi. Dengan begitu, nantinya akan terwujud pendidikan dalam ranah sosial, yaitu yang melahirkan insan-insan paripurna dan bukan sekadar sumber daya manusia (SDM) dalam orientasi ekonomi.
Sejatinya memang pendidikan itu memiliki tujuan kemanusiaan. Pendidikan inklusif ialah pendidikan untuk anak manusia dengan cara-cara yang manusiawi agar menjadi manusia (Paulo Freire: 2008). Sekolah inklusi akan mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, ekonomi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain. Termasuk juga anak korban kekerasan rumah tangga, korban HIV, korban penyalahgunaan narkoba, pekerja anak, gelandangan, anak telantar, anak tunawisma, anak-anak dari daerah terpencil, korban bencana alam, anak-anak jalanan, anak-anak yatim-piatu, atau anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat.
Pendidikan khusus yang awalnya menggunakan model segregasi yang menempatkan PDBK di sekolah khusus seperti sekolah luar biasa (SLB) dan masih dikelompokkan lagi menjadi SL tunanetra (SLB-A), SL tunarungu (SLB-B), SL tunagrahita, SL (SLB-C) tunadaksa (SLB-D), SL tunalaras (SLB-E), dan SL tunaganda (SLB-G) dinilai tidak bisa mengembangkan potensi PDBK secara optimal karena PDBK harus siap berintegrasi dengan masyarakat normal.
Selain biaya untuk masuk sekolah khusus yang relatif kurang terjangkau banyak masyarakat dan membebani peserta didik, pemerintah tidak mungkin membangun SLB di tiap kecamatan atau desa. Para profesional dalam pendidikan luar biasa menilai bahwa penyelenggaraan sekolah dengan dua sistem (sekolah khusus dan sekolah reguler) sebagaimana dilaksanakan di Indonesia sampai saat ini, secara nyata menunjukkan adanya diskriminasi yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, hak-hak asasi manusia, dan dipandang tidak efisien (Marozas dan Deborah: 1998).
Sementara itu, pola pendidikan inklusif diyakini akan mampu menuntun terciptanya universal primary education (UPE), sebagaimana telah dilakukan di Amerika, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, yang telah menerapkan pola tersebut sejak awal 1990-an. Begitu pula di wilayah Asia, seperti Tiongkok, India, Srilanka, dan Nepal (Dr Budiyanto MPd: 2017).
Bahkan, sebetulnya di Indonesia sejak akhir 1990-an, banyak kalangan profesional pendidikan luar biasa sudah mulai ramai membicarakan tentang pendidikan inklusif dalam bentuk seminar-seminar, diskusi panel, dan sejenisnya. Beberapa di antara seminar dan workshop difabel, telah menghasilkan Deklarasi Malioboro, yang intinya meyakini bahwa sistem pendidikan inklusif paling tepat dan perlu direalisasikan (Yogyakarta, 17 Maret 2001). Di Bandung pada pertengahan Mei 2002, kaum difabel menggelar unjuk rasa di hadapan DPRD setempat, salah satu tuntutannya ialah penghapusan sistem eksklusif (SLB) diganti dengan sekolah inklusi.
Tiga langkah
Ada tiga langkah yang dapat dilakukan. Pertama, paradigma berpikir guru Indonesia yang masih konvensional harus diubah. Jika peserta didik mau belajar dengan cara guru mengajar, guru harus mau mengajar dengan cara peserta didik belajar. Guru pembimbing khusus (GPK) atau guru-guru di sekolah inklusi secara konsisten perlu menggeser pola pembelajaran yang kaku berdasarkan teks ke pembelajaran tematik dan pemecahan masalah dengan memberikan layanan prevensi, intervensi, kompensatoris, dan pengembangan potensi peserta didik serta kurikulum seyogianya disesuaikan dengan kebutuhan anak, bukan malah sebaliknya.
Kedua, sekolah harus inklusif dengan menjalin kolaborasi dengan konselor, dokter, psikolog, ahli bahasa, orthopedagoog, dan sistem dukungan seperti pusat sumber (resource center), unit layanan disabilitas (ULD), dan dunia usaha/dunia industri (DUDI). Ketiga, penciptaan sekolah ramah anak (SRA) yang memperhatikan aksesibilitas, desain universal, seperti memperhatikan ketersediaan guiding block, tongkat tunanetra, kursi dengan modifikasi, alat perekam suara, tangga, ramp, atau alat bantu lainnya, classroom management, dan nilai kebersamaan (together value).
Hadiah terindah dan terbaik yang bisa kita berikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus ialah penerimaan, cinta, kepercayaan, dan harapan []
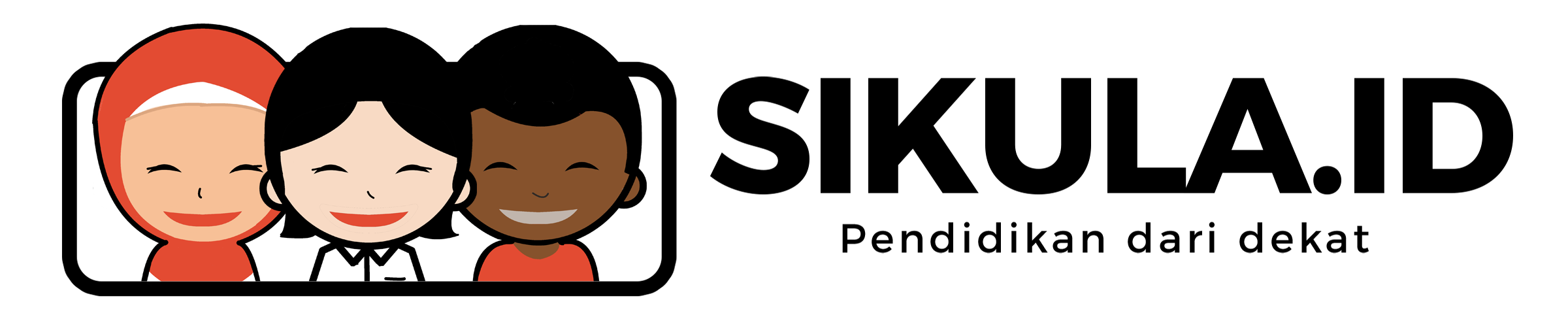

 Sikula id
Sikula id




 Muhammad
Muhammad
 Ayu
Ayu

 Ahmad
Ahmad